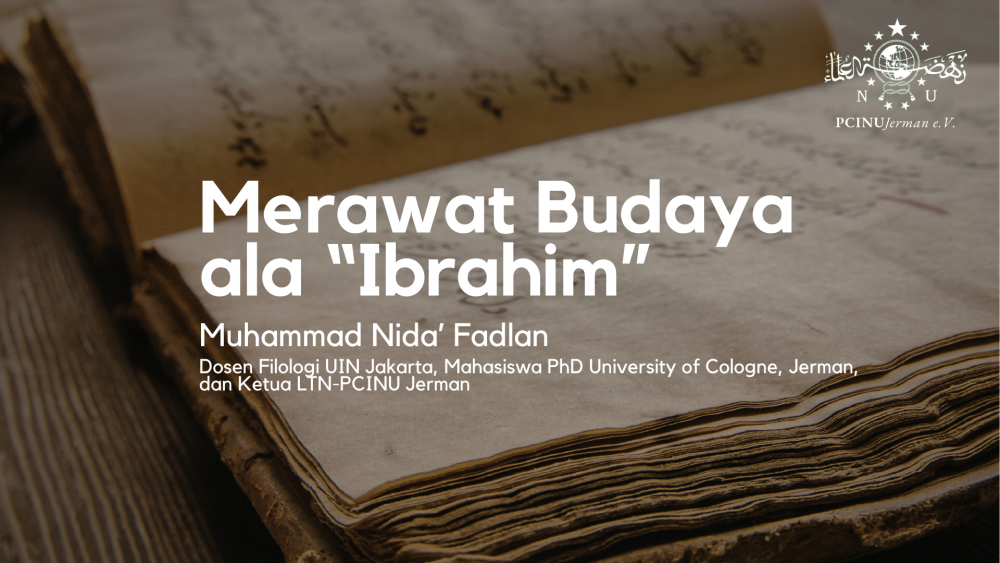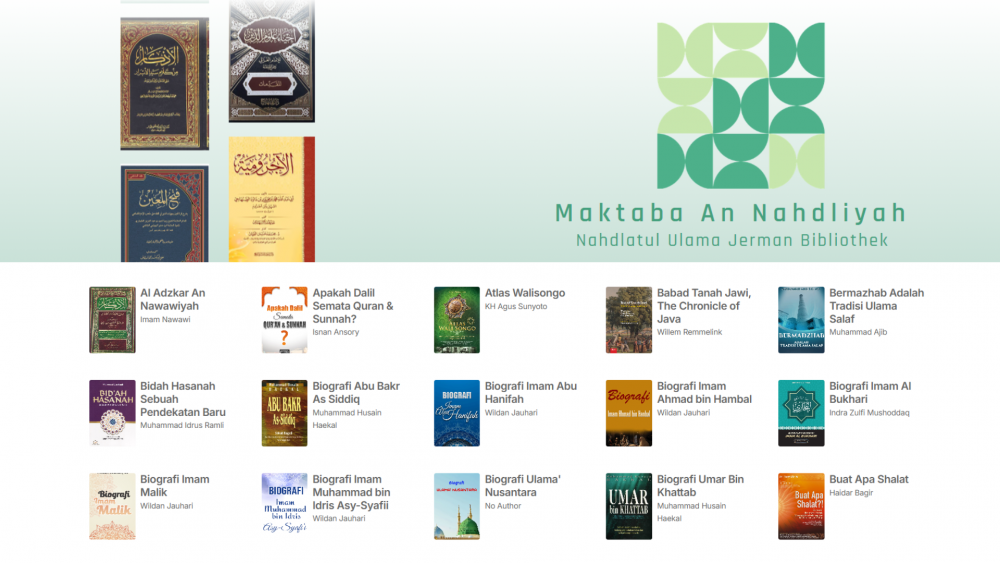Pertanyaan “mengapa kita perlu beragama?” merupakan pertanyaan mendasar yang mungkin terasa kurang relevan di negara dengan tradisi keberagaman dan keberagamaan seperti Indonesia, namun justru selalu menjadi topik hangat di banyak negara Eropa. Di tengah kehidupan modern yang kian perlahan mengalami kemerosotan nilai-nilai moral dan etika (demoralisasi), dimana manusia zaman ini sering kali tersibukkan oleh hal-hal yang tidak penting dan kurang membawa manfaat dalam kehidupan nya, membuat nilai agama saat ini semakin tereduksi dan kian jauh dari substansi ajaran asalnya.
Banyak nya manusia zaman ini baik yang beriman maupun yang tidak beriman, lebih memilih mencari jawaban dari berbagai persoalan hidupnya melalui media sosial. Termasuk ketika menyangkut persoalan keagamaan. Akibatnya, esensi spiritualisme agama mulai terdegradasi dan memudar, karena menurunnya kualitas tradisi transmisi keilmuan dengan semakin berkurangnya pembelajar atau pencari ilmu yang berguru secara langsung dan justru sebaliknya lebih memilih belajar dan mencari pengetahuan secara otodidak sendiri. Inilah kenyataan yang tak dapat disangkal di era modern ini!
Kondisi ini makin terpuruk ketika orang-orang tidak lagi menjalankan praktik keagamaan dan perlahan mulai melepaskan agama nya. Saya ambil contoh di Jerman, di negara saya merantau. Setiap tahun nya jumlah penduduk negara Jerman yang meninggalkan agama terus bertambah. Jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2023 menjadi 46% dari total keseluruhan populasi negara Jerman, yang berarti hampir separuh penduduk negara Jerman saat ini adalah atheis atau agnostis. Mereka keluar dari agama asal mereka yaitu Katholik/Protestan dan memilih untuk tidak beragama sama sekali.
Diskursus mengenai tema keagamaan dan ketuhanan terus menjadi topik yang relevan dan dinamis di Eropa, tak terkecuali di Jerman. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti "Mengapa perlu beragama?", "Apakah agama masih penting?", atau "Apakah Tuhan itu ada dan bagaimana pembuktiannya secara rasional atau ilmiah?" senantiasa muncul dalam wacana sosial, intelektual, dan akademik masyarakat Eropa kontemporer.
Di sinilah peran ilmu teologi menjadi signifikan dalam merespons problematika keimanan dan keagamaan secara sistematis, argumentatif, dan rasional. Meskipun pertanyaan-pertanyaan tersebut terlihat sederhana, pada kenyataannya tidak semua individu mampu menjawabnya secara normatif. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai agama sering kali menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya keraguan terhadap institusi agama dan keberadaan Tuhan. Terlepas bahwa Jerman, seperti juga banyak negara Eropa Barat, mengalami sistem sekularisasi yaitu sebuah proses di mana agama kehilangan pengaruh dalam kehidupan publik dan pribadi. Sehingga nilai-nilai modern seperti individualisme, kebebasan berpikir, dan rasionalisme ilmiah lebih dominan dalam sistem pendidikan dan budaya umum. Juga pengaruh adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap makna dan fungsi agama dalam kehidupan sehari-hari seperti kecenderungan akan merasa bisa “mengatur hidup sendiri” tanpa perlu bergantung pada Tuhan atau pada suatu kepercayaan yang berasal dari agama.
Dalam menjawab pertanyaan ini dari sudut pandang teologis islam, bisa kita pahami bahwa agama memiliki fungsi salah satunya untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus dengan Tuhan sebagai sumber otoritas kebenaran yang memberikan wahyu-Nya kepada manusia. Dalam agama islam, Allah menyampaikan wahyu nya tidak hanya mengenai sesuatu yang bersifat fisik atau bisa diterima akal dan pengetahuan sains belaka, melainkan juga termasuk informasi-informasi metafisik dan spiritual yang tidak dapat diakses melalui akal semata, seperti keberadaan makhluk gaib (jin dan malaikat), ruh, kehidupan setelah kematian, serta norma moral yang berasal dari kehendak Tuhan, yang bukan bersumber atas konstruksi manusia semata.
Tentunya semua informasi ini harus datang dari zat yang bukan termasuk dari mahkluk atau ciptaan-Nya, karena mahkluk contoh halnya kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam berfikir. Sebagaimana manusia secara ontologis yang terlahir kedunia ini diawali dari ketidakpengetahuan seperti yang dikutip dalam QS. An-Nahl: 78 lalu manusia menjadi tahu karena terus belajar dan berkembang kedewasaan akalnya seiring usia. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi dan moralitas, diperlukan referensi transenden yang tidak tunduk pada relativitas sosial, yakni wahyu Tuhan.
Dalam tradisi teologi islam klasik, Imam Abu Hasan al-Ash‘ari, salah satu pendiri mazhab teologi Ahlussunnah wal Jama'ah, menjelaskan dalam karyanya Maqālāt al-Islāmiyyīn, bahwa manusia tidak dapat menetapkan nilai moral secara independen melalui akal semata. Beliau menyatakan bahwa suatu perbuatan dinilai baik atau buruk bukan karena pertimbangan akal dan rasional manusia, melainkan karena wahyu yang ditentukan melalui perintah dan larangan Tuhan. Sebagaimana kutipannya Imam Asyari:
"Manusia tidak dapat membuat penilaian moral terhadap sesuatu tindakan, karena tindakan itu sendiri tidak dapat dinilai secara moral. Manusia melakukan sesuatu karena Allah memerintahkannya, dan meninggalkan sesuatu karena Allah melarangnya.” (Dalam kitab Mujarrad Maqalat Al-Ash'ari)
Dengan demikian, baik dan buruk dalam perspektif teologis menurut Imam Asyari yaitu bersifat teonomik, yaitu berdasarkan pada kehendak Tuhan, bukan otonomik (berbasis akal manusia). Artinya, suatu tindakan dinilai baik bukan karena akal rasionalitas manusia menganggapnya demikian, tetapi karena Tuhan memerintahkannya; dan sebaliknya, sesuatu dianggap buruk karena Tuhan melarangnya.
Misalnya dalam contoh kehidupan sehari-hari, praktik homoseksualitas dalam islam dinilai sebagai sesuatu yang buruk dan tercela karena bertentangan dengan wahyu, walaupun sebagian masyarakat modern seperti di Eropa menganggapnya sah atas dasar hak individu dan kebebasan berekspresi. Demikian pula tindakan pembunuhan. Bagi orang beriman, membunuh tanpa hak adalah dosa besar dan perbuatan yang buruk, akan tetapi, dalam kenyataan sosial, terdapat individu atau kelompok yang mungkin menganggap tindakan tersebut dapat dibenarkan seperti para pelaku kriminal yang mudah mengambil nyawa seseorang atau terjadinya perperangan yang menewaskan banyak nyawa yang tak bersalah yang kita lihat didunia saat ini.
Atau contoh lain untuk memperjelas relativitas penilaian moral bila dilepaskan dari wahyu, bayangkan sebuah eksperimen ilustrasi: seorang anak manusia dibesarkan di hutan secara terisolasi, tanpa akses terhadap pendidikan, budaya, atau agama. Ia tetap memiliki fitrah (naluri dasar) dan akal sebagai bagian dari kodrat manusia. Namun, ketika ia pertama kali bertemu manusia asing dan merasa terancam, respons yang mungkin muncul secara naluriah adalah tindakan membunuh sebagai bentuk pertahanan diri. Padahal, dalam konteks masyarakat beradab, tindakan tersebut bisa dipandang sebagai perbuatan yang salah atau melanggar moral.
Kondisi ini menunjukkan bahwa akal dan naluri manusia memiliki keterbatasan dalam menilai moralitas, dan sekalipun manusia menggunakan akal yang sama sebagai instrumen pengetahuan, hasil penilaiannya dapat sangat bervariasi jika tidak dikaitkan dengan referensi moral yang satu oleh Tuhan. Oleh karena itu, agama melalui wahyu berperan sebagai otoritas moral yang menyatukan panduan hidup dan memastikan keadilan serta kesetaraan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial yang memiliki keberagaman pemikiran, identitas dan latar belakangnya. Islam dengan jelas menegaskan bahwa sumber kebenaran moral yang paling otoritatif dan stabil adalah wahyu Tuhan, bukan konstruksi rasional manusia yang besifat relatif dan dinamis yang bisa berubah-ubah sesuai konteks dan zaman.
Dalam konteks masyarakat sekuler seperti Jerman, peran teologi tetap krusial sebagai penjaga nilai-nilai spiritual dan moral di tengah krisis makna yang ditimbulkan oleh rasionalisme ekstrem dan relativisme moral. Agama, dalam hal ini islam, menawarkan kerangka berpikir yang menyeluruh, bukan hanya menyangkut hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antarsesama manusia. Oleh karena itu, mendialogkan agama dan rasionalitas secara kritis dan terbuka menjadi tugas penting di era modern agar makna spiritualitas tidak sepenuhnya terpinggirkan dalam peradaban kontemporer.
Wa minaAllahi tawfiq.
Osnabrück, 15 Syaban 1447H